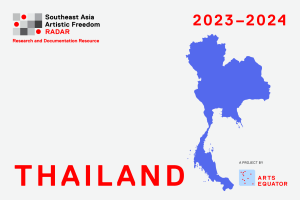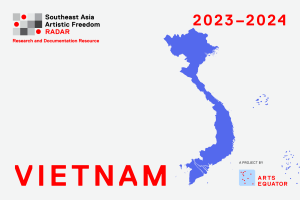Laporan analisis dan temuan kunci kebebasan artistik di Indonesia dari Southeast Asia Artistic Freedom RADAR, 2023–2024.
'The boys are back in town'
Setelah pandemi dan Jokowi, kediktatoran lawas bersemi kembali
Kebebasan artistik di Indonesia bertautan erat dengan kualitas demokrasi yang dalam peralihan kekuasaan baru-baru ini mengalami terjun bebas. Setelah menjabat selama satu dekade, Joko Widodo, presiden sipil pertama Indonesia yang awalnya dianggap sebagai angin segar, nyaris melumpuhkan demokrasi Indonesia dalam usahanya untuk terus berkuasa lewat dari dua periode. Prabowo Subianto, dahulu rival dan sekarang penerusnya, hampir tidak menawarkan perbaikan. Terpilih pada November 2024, berbagai kelompok masyarakat melihat Prabowo sebagai penerus tren perusakan demokrasi. Anggapan ini lahir utamanya dari hubungan erat sang jenderal dengan rezim diktator dan militer Suharto, serta perannya dalam penculikan beberapa aktivis politik pada dekade 1990-an. Sesuai dugaan, salah satu keputusan pertama Prabowo setelah berkuasa adalah memberi lampu hijau untuk undang-undang yang memperbesar peran militer di pemerintahan, meniru dwifungsi peran militer selama tirani Suharto dari 1967 hingga 1998. Agenda berikutnya: undang-undang serupa yang meningkatkan kekuasaan polisi.
Tren opresif ini mewujud dalam kasus pelanggaran seni yang menjadi sorotan luas pada awal tahun ini. Pada Februari 2025, Sukatani, band punk yang selalu memakai topeng saat manggung, menunjukkan wajah mereka dalam video permintaan maaf publik kepada kapolri, setelah kabarnya berbulan-bulan mendapatkan pengawasan dan tekanan dari kepolisian. Sasarannya adalah “Bayar Bayar Bayar”, lagu Sukatani yang cukup dikenal dan mengkritisi polisi nakal yang kerap menyalahgunakan otoritas mereka. Dalam video permintaan maaf, Sukatani menyebutkan bahwa lagu ini akan dihapus dari platform streaming musik. Namun, dampak yang diharapkan tidak terwujud—“Bayar Bayar Bayar” dan lagu-lagu Sukatani lainnya justru makin populer dan sering diputar. Orang-orang bahkan menyanyikannya di jalanan sebagai lagu tema dalam demo besar-besaran menolak wacana undang-undang militer.
Kasus Sukatani adalah titik berangkat yang baik untuk memahami gambaran terkini tentang kebebasan artistik di Indonesia, terutama mengingat dua tahun terakhir yang menunjukkan tren serupa perihal intrusi negara ke kehidupan sipil. Dari 67 kasus pelanggaran seni yang dicatat ArtsEquator, 30 kasus terjadi pada 2023 dan 37 pada 2024, dan 48 dari kasus tersebut dipimpin oleh agen pemerintahan, atau sekitar 70% dari total kasus. Sebanyak 29 kasus melibatkan lembaga penegak hukum, kebanyakan kepolisian, sementara 14 kasus melibatkan otoritas di luar ranah seni, sering kali lembaga pemerintahan lokal. Pola opresif ini bisa dibilang bermula cukup awal pada pandemi tahun 2020 hingga 2022, dengan 36 kasus dimulai oleh lembaga pengawas baru, Satgas Penanganan COVID-19, yang sering bekerja sama dengan militer dan kepolisian setempat. Dalam periode yang sama, pendukung dan loyalis Presiden Jokowi terang-terangan memunculkan wacana tiga periode—sebuah manuver politik yang sejatinya menyalahi konstitusi. Meski akhirnya gagal, upaya perwujudan wacana tiga periode tersebut cukup efektif dalam melemahkan pihak oposisi dan memindahkan lebih banyak kekuasaan ke lembaga penegak hukum.
Namun, kehadiran pelaku sensor dari pemerintahan merupakan perkembangan baru. Selain kasus yang terjadi selama pandemi, ArtsEquator mencatat 92 kasus dari 2010 hingga 2022. Sebanyak 50 dari total kasus melibatkan setidaknya satu kelompok masyarakat sipil sebagai pelaku sensor, dengan 13 kasus yang utamanya digerakkan oleh kelompok masyarakat sipil, sementara 37 kasus melibatkan kelompok masyarakat sipil dan lembaga pemerintahan atau lembaga pengawas sebagai aktor utama. Kasus-kasus tersebut mewakili lebih dari separuh total kasus yang terjadi di Indonesia pada periode tersebut. Bertolak belakang, pada 2023 dan 2024, terdapat 13 kasus yang melibatkan kelompok masyarakat sipil dalam berbagai kapasitas, jumlah yang hanya menyumbang 20% dari total kasus dalam dua tahun terakhir.
Kasus Sukatani juga memperlihatkan pergeseran lain yang penting dengan musik yang menjadi medium paling disasar dalam dua tahun terakhir (19 pada 2023, 25 pada 2024). Sebelumnya, dari 2010 hingga 2022, film adalah medium yang menjadi sasaran utama, yaitu 27 dari 128 kasus. Menyusul dengan angka yang tidak jauh berbeda adalah seni visual dengan 24 kasus, seni pertunjukan dengan 24 kasus, dan musik dengan 21 kasus. Lanskap kebebasan artistik dalam dua tahun terakhir tampak lebih mengerucut, karena musik menjadi satu-satunya medium yang terkena lebih dari 10 kasus, diikuti oleh film dan praktik kebudayaan atau warisan budaya dengan masing-masing 7 kasus. Musik jauh melampaui medium lainnya dengan 44 kasus.
Penyebab dinamika tersebut adalah Sumatra Selatan. Provinsi ini menyumbang 23 kasus atau lebih dari separuh insiden di ranah musik dalam dua tahun terakhir—12 pada 2023 dan 11 pada 2024. Situasi ini bermula dari surat edaran kapolda tentang pelarangan musik remix dan elektronik, yang menyatakan bahwa kedua genre tersebut sering memicu tindakan kriminal seperti penggunaan obat-obatan dan kekerasan. Meskipun tidak mengikat secara hukum, arahan ini mendorong kepolisian daerah untuk menyisir semua acara perkumpulan atau acara publik yang memainkan musik bergenre remix atau elektronik, entah itu konser standar, pernikahan, atau upacara sunat.
Di konteks lokal, pelarangan di tingkat provinsi ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa Sumatra Selatan merupakan penyumbang terbesar kedua untuk angka penyalahgunaan narkotika dari seluruh provinsi di Indonesia. Fakta tersebut melandasi pernyataan publik yang dibuat oleh kapolda dan Badan Narkotika Nasional, sebelum munculnya surat edaran. Dengan kata lain, seni dan praktik budaya menjadi sasaran kolateral dari pergulatan melawan narkotika.
Hal ini membawa kita pada karakteristik lain yang muncul lewat kasus Sukatani: desentralisasi penyensoran oleh negara. Meskipun kasusnya berujung mendapat sorotan nasional, penargetan dan pemaksaan pembuatan video permintaan maaf Sukatani dilakukan oleh salah satu unit dalam kepolisian daerah Jawa Tengah. Kondisi serupa bisa ditemukan di banyak pelanggaran hak artistik pada 2023 dan 2024. Total, ada 48 kasus dalam dua tahun terakhir yang dalangnya merupakan pelaku sensor dari pemerintahan. Sebanyak 45 kasus tersebut menyebutkan pelaku sensor dari lokal atau daerah di tahap awal penyensoran, menyumbang 94% dari total kasus selama periode itu.
Secara umum, tren ini mengikuti tren desentralisasi dari tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kasus dari kota-kota besar atau ibu kota provinsi hanya menyumbang sepertiga dari kasus penyensoran seni dari 2010 hingga 2022. Sebagai konteks, pemerintahan daerah di Indonesia biasanya dibagi ke dalam empat tingkat administrasi. Tingkat pertama adalah pemerintahan provinsi, yang langsung melapor ke pemerintahan nasional. Provinsi terdiri dari kota dan kabupaten, yang merupakan tingkat kedua dalam subdivisi. Setiap kota dan kabupaten memiliki beberapa kecamatan yang membentuk tingkat ketiga dalam pemerintahan daerah. Kecamatan bisa dibentuk oleh beberapa desa, baik yang berlokasi di area rural maupun urban, dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa terpilih, dan merupakan tingkat paling bawah dalam subdivisi. Sebagian besar kasus penyensoran seni dari 2010 hingga 2022 terjadi di tingkat ketiga dan keempat dalam pemerintahan daerah, sebagaimana yang juga terjadi selama dua tahun terakhir.
Namun, terdapat pergeseran mencolok di antara kedua periode itu, dengan pandemi sebagai titik balik yang vital. Sebelum pandemi, kekuatan berpusat pada eselon atas, dengan pemerintah kabupaten atau kota di posisi terbawah, sebagaimana didukung oleh undang-undang otonomi daerah. Lebih bawah lagi, otoritas pemerintahan tidak begitu hadir dan badan penegak hukum pun lebih lunak, atau sama sekali tidak menampakkan diri. Kondisi ini memungkinkan seniman untuk berkarya jauh dari pengawasan negara, meski di sisi lain juga membuat pelaku sensor dari masyarakat sipil lebih berani bertindak sebagai hakim dan algojo. Inilah yang paling sering terjadi sebelum 2020. COVID-19 dan angka kematian yang terus bertambah memaksa pemerintahan pusat untuk lebih memantau kecamatan dan kelurahan melalui satgas pandemi. Militer dan kepolisian dengan segera menjadi penindas rutin di area-area tersebut; mereka acap membubarkan kegiatan seni dengan mengatasnamakan kesehatan dan keamanan publik.
Dinamika kuasa ini, yang awalnya merupakan respons darurat, terus berlanjut dan dilanggengkan oleh rezim hingga jauh setelah pandemi berakhir. Meningkatnya kewaspadaan di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi mendorong penegak hukum untuk menjangkau lebih luas dan lebih dalam, tercermin dalam banyaknya kasus di tingkat lokal dan daerah. Pada bulan-bulan awal, pemerintahan Prabowo pada dasarnya melanjutkan tren ini dengan meresmikan beberapa metode yang dimulai oleh rezim sebelumnya. Oleh karena itu, kasus Sukatani bisa dianggap sebagai puncak sekaligus awal. Kasus ini merangkum kecenderungan opresif beberapa tahun belakangan sekaligus menunjukkan kemungkinan yang akan datang. Apabila tak ada goncangan berarti dalam konstelasi kekuasaan di Indonesia, kasus-kasus serupa mungkin akan bermunculan ke depannya.
(This article was translated by Ukky Satya. Read the original report by Adrian Jonathan Pasaribu here.)
REFERENSI
“Laporan Khusus: Catatan Akhir Tahun 2023, Sumsel Masih Darurat Narkoba”, rmolsumsel.id, 29/12/2023
“Punk band Sukatani removes viral song from streaming services”, thejakartapost.com, 21/2/2025
Amelia Rahima Sari, “Prabowo Says He’ll Closely Scrutinize Police Bill Amid Public Concern”, tempo.co, 8/4/2025
Annisa Febiola, “Bentuk-Bentuk Intimidasi yang Diterima Band Sukatani Sejak Juli 2024”, tempo.co, 2/3/2025
Emma Connors & Natalia Santi, “Why Indonesia’s president is angling for a third term”, afr.com, 11/3/2022
Kelly Ng & Silvano Hajid, “Anger as Indonesia law allows military bigger role in government”, bbc.com, 20/3/2025
Sana Jaffrey & Eve Warburton, “Prabowo’s Indonesia: Inheriting Democracy at Dusk”, carnegieendowment.org, 22/10/2024

Adrian Jonathan Pasaribu
Adrian Jonathan Pasaribu is the chief editor and co-founder of Cinema Poetica—a collective of film critics, activists, and researchers in Indonesia. In 2013, Adrian participated in Berlinale Talent Campus as a film critic, and since then regularly organized or mentored film criticism workshops in Indonesia. He has also curated several film festivals, including Festival Film Dokumenter, Jogja-NETPAC Asian Film Festival, and Singapore International Film Festival. In 2020, as part of Cinema Poetica, Adrian contributed several writings for Antarkota Antarlayar: Potret Komunitas Film di Indonesia (Between Cities and Screens: Film Communities in Indonesia), a book published by Jakarta Arts Council.
- Adrian Jonathan Pasaribu
- Adrian Jonathan Pasaribu
- Adrian Jonathan Pasaribu
- Adrian Jonathan Pasaribu
Similar Reads